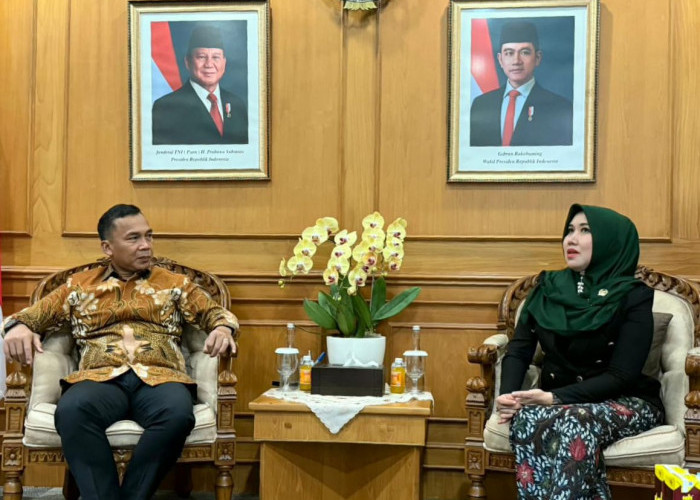Bilik Suara Vs Bilik Dewan

Fatkhul Aziz--
Mungkin demokrasi memang sebuah bangunan yang tak pernah selesai, sebuah proyek yang terbengkalai, seperti yang pernah dikatakan seorang pemikir. Di sana ada keringat, ada teriakan, dan kadang-kadang, ada bau amis kecemasan. Hari-hari ini, kecemasan itu kembali datang, samar tapi pasti, seperti kabut yang merayap di kaki jurang.
Kita mendengar sebuah orkestra sedang dimainkan. Dirigennya adalah mereka yang duduk di kursi-kursi empuk kekuasaan, dan partiturnya adalah sebuah hasrat lama: mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan para wakil rakyat di DPRD. "Demi efisiensi," kata mereka. "Demi ketertiban," dalih yang lain.
BACA JUGA:Kembali ke Bumi

Mini Kidi--
Namun, kita tahu, di balik kata-kata yang rapi itu, ada sesuatu yang sedang dicuri dari tangan orang banyak.
Alasannya terdengar masuk akal—dan itulah yang membuatnya berbahaya. Mereka menunjuk ke arah gedung KPK. Mereka menghitung jumlah bupati dan walikota yang digelandang dengan rompi oranye. Korupsi, kata para politisi ini, adalah anak kandung dari pemilihan langsung yang berbiaya mahal. Maka, obatnya adalah menutup kotak suara di lapangan-lapangan desa dan memindahkannya ke ruang-ruang sidang yang tertutup di gedung dewan.
BACA JUGA:Pesta Pasti Berakhir
Tapi benarkah demikian? Benarkah racun itu ada pada hak rakyat untuk memilih, dan bukan pada mereka yang rakus memburu kursi?
Sejarah sering kali mengajarkan bahwa ketika kedaulatan "disederhanakan", yang sebenarnya terjadi adalah penyempitan ruang hidup. Demokrasi yang dipindahkan ke tangan segelintir elite—apa yang mereka sebut sebagai perwakilan—sering kali berubah menjadi transaksi di ruang remang-remang. Di sana, suara rakyat tak lagi berupa harapan, melainkan angka-angka dalam buku kas partai.
Kita seakan sedang dipaksa percaya bahwa karena ada beberapa pilot yang mabuk, maka pesawatnya yang harus dihancurkan, dan kita semua harus kembali berjalan kaki di bawah kendali mandor.
BACA JUGA:Super Flu
Jika Pilkada dihapuskan, kita bukan sedang memperbaiki demokrasi yang sakit. Kita sedang membangun sebuah teater bisu. Rakyat hanya akan menjadi penonton di luar pagar, menyaksikan nasib mereka ditentukan oleh kesepakatan-kesepakatan di bawah meja, oleh lobi-lobi yang tak pernah mereka dengar, dan oleh kepentingan yang tak pernah melibatkan perut mereka yang lapar.
Demokrasi memang berisik. Ia kotor, ia mahal, dan ia sering kali mengecewakan. Tapi di dalam kegaduhan itu, ada sebuah pengakuan yang paling dasar: bahwa setiap manusia, tak peduli betapa jelatanya, memiliki hak untuk menentukan siapa yang memimpin hidupnya.
Ketika hak itu dicabut dengan alasan "ketertiban" atau "pencegahan korupsi" yang diatur oleh mereka yang juga rawan korupsi, kita tahu kita sedang berdiri di bibir jurang.
Sumber: