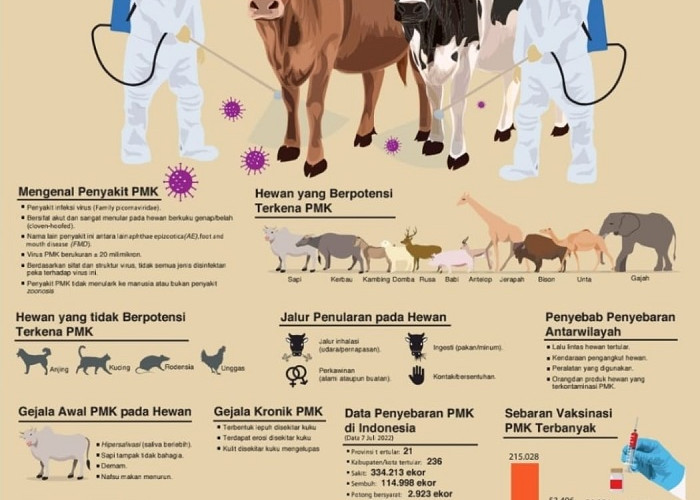Uang Mengalir

 Mungkin ada yang berpendapat begini: tidak peduli utang atau cetak uang, yang penting uangnya dibagi untuk kita-kita.
Seperti juga prinsip ”amplop merah itu tidak penting, yang penting isinya”.
Maka utang atau pun cetak uang, yang penting uangnya akan dialirkan ke mana?
Kalau utang, yang akan terima uang adalah kementerian keuangan. Masuk APBN. Dari sini uang hasil utang bisa dialirkan ke mana saja --sesuai dengan program pemerintah.
Kalau cetak uang, hasil cetak uang itu menjadi milik bank sentral --Bank Indonesia.
Maka, kalau keputusannya nanti cetak uang, dari mana pemerintah dapat uang? Pinjam ke BI? Kan tidak ada pintunya?
Berarti pemerintah memang benar-benar sulit --harus lebih banyak kita doakan. Mau cari utang, sulit. Tidak mudah cari utangan di situasi sekarang --semua negara mau utang. Mau cetak uang, uangnya menjadi milik Bank Indonesia.
Sekarang sudah berbeda dengan zaman tahun 1956. Ketika itu pemerintah bisa memerintahkan cetak uang. Sekarang tidak bisa lagi. Bank Indonesia itu independen.
Bahkan Bank Indonesia sendiri tidak bisa cetak uang begitu saja. Bank Indonesia itu diadakan dengan tugas khusus yang tunggal: menjaga nilai mata uang rupiah.
Tidak ada lagi tugas lain dari BI. Tugas lamanya yang satu itu --sebagai Stasiun Balapan, lender of the last resort-- sudah dihapus.
BI tidak boleh lagi jadi sandaran akhir bank-bank pelaksana. Tidak ada lagi sumber dana yang dulu disebut ”Bantuan Likuiditas Bank Indonesia” itu. Bank yang mengalami kesulitan uang sudah punya tempat sendiri untuk meminjam.
Itulah sebabnya tidak mudah bagi BI didesak untuk cetak uang. Setiap cetak uang pasti akan memerosotkan nilai mata uang rupiah --inflasi.
Kalau sampai itu terjadi berarti BI telah gagal melakukan tugas satu-satunya.
Tapi tanpa cetak uang BI kan juga gagal menjaga nilai mata uang? Bulan lalu? Sampai satu dolar menjadi Rp 16.000?
Orang seperti Mukhamad Misbakhun akan menggunakan lubang seperti itu untuk berargumentasi. ”Harus saya akui Misbakhun sangat pintar,” ujar Prof. Didik Rachbini dari INDEF kepada saya kemarin.
Prof Didik, Misbakhun, dan saya memang jadi pembicara dalam Webinar Sabtu lalu. Soal ekonomi pasca Covid-19. Yang diadakan oleh Pengurus Pusat KB PII --organisasi alumnus Pelajar Islam Indonesia.
Di situlah Misbakhun menjelaskan konsep pemikirannya untuk cetak uang. Yang kemudian menjadi sikap DPR. Sedang Prof Didik Rachbini menjelaskan bahayanya cetak uang.
Di forum KB PII itu, sikap Misbakhun jelas: BI harus cetak uang.
”Ia pinter. Ia tidak menyebut cetak uang. Ia menamakannya quantitative easing,” ujar Prof. Didik. ”Seperti di Amerika saja,” tambahnya.
Menurut Misbakhun, hasil cetak uang itu disalurkan ke bank-bank pelaksana. Dipinjamkan ke bank. Sebagai pinjaman khusus. Dengan bunga khusus --yang sangat murah. Bahkan harus 0 persen --karena BI tidak boleh berbisnis.
Lantas bank meminjamkan dana itu ke pengusaha. Dengan bunga sangat murah. Misalnya 2 persen.
Pengusaha lantas menggunakannya untuk menggerakkan perusahaan --menciptakan lapangan kerja.
Ekonomi pun bergerak.
Sampai di sini akan terjadi perdebatan yang panjang: pengusaha mana yang bisa mendapat kredit khusus dengan bunga khusus itu.
Untuk UKM? Perusahaan umum? Perusahaan besar? Atau siapa saja yang selama ini punya pinjaman ke bank yang tidak bisa membayar --karena Covid-19?
Bagaimana dengan perusahaan yang sebelum ada Covid-19 pun sudah sempoyongan?
Belum lagi: berapa sebenarnya kebutuhan uang semua pengusaha besar dan kecil itu? Agar cetak uangnya cukup?
Lalu: siapa yang akan menghitung kebutuhan uang itu? Lewat mekanisme apa? Mekanisme bank?
Kalau ternyata kebutuhan itu, misalnya, mencapai 2.000 triliun rupiah, apakah BI akan cetak uang sebanyak itu?
Pasti rupiah langsung terjun bebas.
Maka Prof. Didik menawarkan jalan kompromi: cetak uangnya sedikit dulu. ”Kalau harus cetak uang, haruslah bertahap. Sedikit-sedikit dulu,” ujar Prof Didik.
Misbakhun pun setuju dengan usul itu. Ternyata Misbakhun juga bisa mendengarkan ide dari Prof. Didik itu.
Belum selesai. Persoalan pun timbul. Tidak kalah krusialnya. Siapa yang mendapat prioritas mendapatkan uang yang ”sedikit” itu?
Kalau cetak uangnya sedikit, untuk UKM pun tidak cukup. Apalagi menjangkau yang besar.
Kalau hanya sebagian kecil UKM yang bisa mendapatkannya: siapa yang sedikit itu? Siapa yang menentukan?
Rasanya cetak uang pun ternyata akan menemukan jalan buntu --di tingkat pelaksanaan. Kecuali, tidak usah mempertimbangkan fair atau tidak, adil atau tidak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun rupanya sudah membayangkan kesulitan di tingkat detail seperti itu.
Tapi lantas apa?
Sudah jelas, mencari pinjaman juga sulit. Mengeluarkan obligasi tidak lagi laku.
Kementerian Keuangan pun memutuskan untuk cari jalan lain: menjual obligasi ke Bank Indonesia. Menurut Prof. Didik nilai obligasi itu mencapai Rp 150 triliun.
Apakah boleh pemerintah menjual obligasi dan menugaskan BI agar membelinya?
Sebenarnya itu sama saja dengan Kementerian Keuangan memerintahkan BI untuk mencetak uang. Sebanyak Rp 150 triliun itu.
Tentu BI akan menolak permintaan seperti itu. Selama ini BI berpegang pada UU yang mengatur dirinya. Yang melarang perbuatan seperti itu.
Tapi pemerintah kini menerobos aturan itu. Dengan cara yang kita semua sudah tahu: lewat Perppu baru, yang disahkan kemarin itu.
Ups... Serba sulit.
Berarti tidak lagi hanya politisi (DPR) yang berhadapan dengan teknokrat di pemerintahan. Teknokrat yang di kementerian pun harus berhadapan dengan teknokrat yang ada di Bank Indonesia.
Belum ada jalan keluar.
Bagi kita, ternyata lebih enak kalau Tung Desem saja yang kembali beraksi: menyebar uang kontan dari udara. (Dahlan Iskan)
Mungkin ada yang berpendapat begini: tidak peduli utang atau cetak uang, yang penting uangnya dibagi untuk kita-kita.
Seperti juga prinsip ”amplop merah itu tidak penting, yang penting isinya”.
Maka utang atau pun cetak uang, yang penting uangnya akan dialirkan ke mana?
Kalau utang, yang akan terima uang adalah kementerian keuangan. Masuk APBN. Dari sini uang hasil utang bisa dialirkan ke mana saja --sesuai dengan program pemerintah.
Kalau cetak uang, hasil cetak uang itu menjadi milik bank sentral --Bank Indonesia.
Maka, kalau keputusannya nanti cetak uang, dari mana pemerintah dapat uang? Pinjam ke BI? Kan tidak ada pintunya?
Berarti pemerintah memang benar-benar sulit --harus lebih banyak kita doakan. Mau cari utang, sulit. Tidak mudah cari utangan di situasi sekarang --semua negara mau utang. Mau cetak uang, uangnya menjadi milik Bank Indonesia.
Sekarang sudah berbeda dengan zaman tahun 1956. Ketika itu pemerintah bisa memerintahkan cetak uang. Sekarang tidak bisa lagi. Bank Indonesia itu independen.
Bahkan Bank Indonesia sendiri tidak bisa cetak uang begitu saja. Bank Indonesia itu diadakan dengan tugas khusus yang tunggal: menjaga nilai mata uang rupiah.
Tidak ada lagi tugas lain dari BI. Tugas lamanya yang satu itu --sebagai Stasiun Balapan, lender of the last resort-- sudah dihapus.
BI tidak boleh lagi jadi sandaran akhir bank-bank pelaksana. Tidak ada lagi sumber dana yang dulu disebut ”Bantuan Likuiditas Bank Indonesia” itu. Bank yang mengalami kesulitan uang sudah punya tempat sendiri untuk meminjam.
Itulah sebabnya tidak mudah bagi BI didesak untuk cetak uang. Setiap cetak uang pasti akan memerosotkan nilai mata uang rupiah --inflasi.
Kalau sampai itu terjadi berarti BI telah gagal melakukan tugas satu-satunya.
Tapi tanpa cetak uang BI kan juga gagal menjaga nilai mata uang? Bulan lalu? Sampai satu dolar menjadi Rp 16.000?
Orang seperti Mukhamad Misbakhun akan menggunakan lubang seperti itu untuk berargumentasi. ”Harus saya akui Misbakhun sangat pintar,” ujar Prof. Didik Rachbini dari INDEF kepada saya kemarin.
Prof Didik, Misbakhun, dan saya memang jadi pembicara dalam Webinar Sabtu lalu. Soal ekonomi pasca Covid-19. Yang diadakan oleh Pengurus Pusat KB PII --organisasi alumnus Pelajar Islam Indonesia.
Di situlah Misbakhun menjelaskan konsep pemikirannya untuk cetak uang. Yang kemudian menjadi sikap DPR. Sedang Prof Didik Rachbini menjelaskan bahayanya cetak uang.
Di forum KB PII itu, sikap Misbakhun jelas: BI harus cetak uang.
”Ia pinter. Ia tidak menyebut cetak uang. Ia menamakannya quantitative easing,” ujar Prof. Didik. ”Seperti di Amerika saja,” tambahnya.
Menurut Misbakhun, hasil cetak uang itu disalurkan ke bank-bank pelaksana. Dipinjamkan ke bank. Sebagai pinjaman khusus. Dengan bunga khusus --yang sangat murah. Bahkan harus 0 persen --karena BI tidak boleh berbisnis.
Lantas bank meminjamkan dana itu ke pengusaha. Dengan bunga sangat murah. Misalnya 2 persen.
Pengusaha lantas menggunakannya untuk menggerakkan perusahaan --menciptakan lapangan kerja.
Ekonomi pun bergerak.
Sampai di sini akan terjadi perdebatan yang panjang: pengusaha mana yang bisa mendapat kredit khusus dengan bunga khusus itu.
Untuk UKM? Perusahaan umum? Perusahaan besar? Atau siapa saja yang selama ini punya pinjaman ke bank yang tidak bisa membayar --karena Covid-19?
Bagaimana dengan perusahaan yang sebelum ada Covid-19 pun sudah sempoyongan?
Belum lagi: berapa sebenarnya kebutuhan uang semua pengusaha besar dan kecil itu? Agar cetak uangnya cukup?
Lalu: siapa yang akan menghitung kebutuhan uang itu? Lewat mekanisme apa? Mekanisme bank?
Kalau ternyata kebutuhan itu, misalnya, mencapai 2.000 triliun rupiah, apakah BI akan cetak uang sebanyak itu?
Pasti rupiah langsung terjun bebas.
Maka Prof. Didik menawarkan jalan kompromi: cetak uangnya sedikit dulu. ”Kalau harus cetak uang, haruslah bertahap. Sedikit-sedikit dulu,” ujar Prof Didik.
Misbakhun pun setuju dengan usul itu. Ternyata Misbakhun juga bisa mendengarkan ide dari Prof. Didik itu.
Belum selesai. Persoalan pun timbul. Tidak kalah krusialnya. Siapa yang mendapat prioritas mendapatkan uang yang ”sedikit” itu?
Kalau cetak uangnya sedikit, untuk UKM pun tidak cukup. Apalagi menjangkau yang besar.
Kalau hanya sebagian kecil UKM yang bisa mendapatkannya: siapa yang sedikit itu? Siapa yang menentukan?
Rasanya cetak uang pun ternyata akan menemukan jalan buntu --di tingkat pelaksanaan. Kecuali, tidak usah mempertimbangkan fair atau tidak, adil atau tidak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pun rupanya sudah membayangkan kesulitan di tingkat detail seperti itu.
Tapi lantas apa?
Sudah jelas, mencari pinjaman juga sulit. Mengeluarkan obligasi tidak lagi laku.
Kementerian Keuangan pun memutuskan untuk cari jalan lain: menjual obligasi ke Bank Indonesia. Menurut Prof. Didik nilai obligasi itu mencapai Rp 150 triliun.
Apakah boleh pemerintah menjual obligasi dan menugaskan BI agar membelinya?
Sebenarnya itu sama saja dengan Kementerian Keuangan memerintahkan BI untuk mencetak uang. Sebanyak Rp 150 triliun itu.
Tentu BI akan menolak permintaan seperti itu. Selama ini BI berpegang pada UU yang mengatur dirinya. Yang melarang perbuatan seperti itu.
Tapi pemerintah kini menerobos aturan itu. Dengan cara yang kita semua sudah tahu: lewat Perppu baru, yang disahkan kemarin itu.
Ups... Serba sulit.
Berarti tidak lagi hanya politisi (DPR) yang berhadapan dengan teknokrat di pemerintahan. Teknokrat yang di kementerian pun harus berhadapan dengan teknokrat yang ada di Bank Indonesia.
Belum ada jalan keluar.
Bagi kita, ternyata lebih enak kalau Tung Desem saja yang kembali beraksi: menyebar uang kontan dari udara. (Dahlan Iskan)
Sumber: