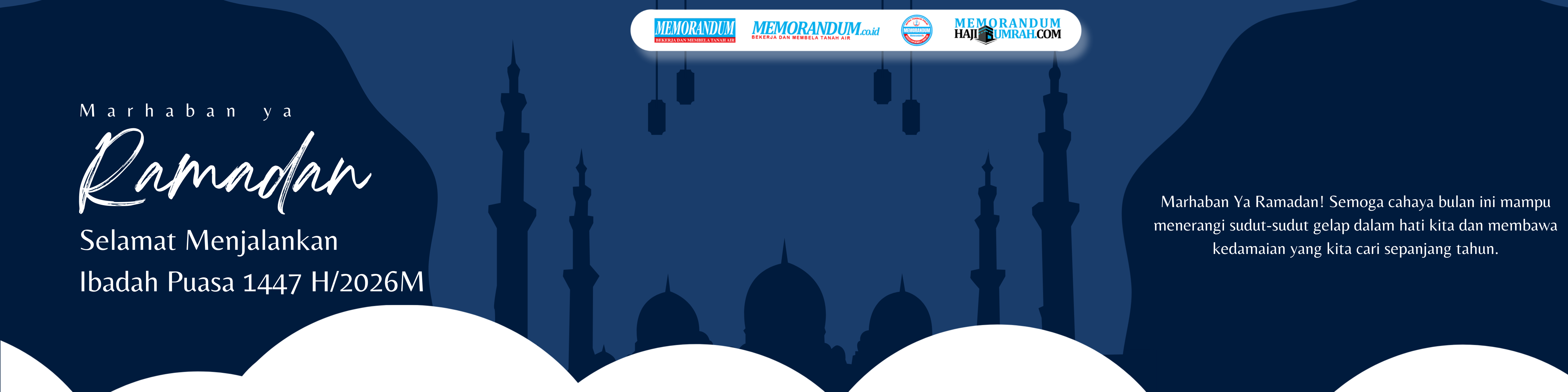Anak Bukan Konten: Toxic Parenting di Media Sosial

Catatan Redaksi Anis Tiana Pottag.--
Media sosial seharusnya menjadi ruang berbagi, bukan ruang memajang anak tanpa batas. Namun beberapa tahun terakhir, muncul fenomena yang mengkhawatirkan: orang tua yang menjadikan anak sebagai konten, komoditas, bahkan aset digital. Setiap tawa anak direkam, setiap tangis diunggah, setiap kesalahan dipublikasikan bukan untuk mendidik, melainkan demi likes, views, dan monetisasi.
BACA JUGA:Bobi Bos! Hajat Hidup Orang Banyak Dikuasai Negara

Mini Kidi--
Fenomena ini disebut sebagai toxic parenting digital, sebuah pola asuh yang tampak modern tetapi membawa dampak psikologis dan hukum yang mengerikan. Lebih ironis lagi, banyak orang tua melakukannya dengan dalih cinta: “Kan supaya lucu,” “biar nanti punya kenangan,” atau bahkan “ini demi masa depan mereka.” Padahal di balik layar, anak justru kehilangan ruang aman ruang yang seharusnya menjaganya dari sorotan publik.
BACA JUGA:Smart City Tanpa Smart People Hanya Jadi Proyek Hiasan
Anak pada dasarnya tidak pernah meminta menjadi selebritas di usia dini. Mereka tidak bisa memberi persetujuan, tidak memahami konsekuensi digital, dan tidak memiliki kuasa atas jejak digital yang dibangun atas nama “kedekatan keluarga.” Ketika orang tua mempublikasikan tantrum, nilai rapor, momen mandi, hingga ekspresi malu sang anak, yang hilang bukan hanya privasi tetapi juga martabat.
BACA JUGA:Datang Diam-diam, Pulang Membawa Nama Besar
Dalam konteks hukum, Indonesia sebenarnya sudah memberi tanda peringatan keras. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang eksploitasi anak dalam bentuk apa pun, termasuk secara digital. UU ITE dan UU PDP menempatkan foto, video, dan data anak sebagai data sensitif yang wajib dilindungi. Artinya, orang tua sekalipun tidak boleh sembarangan mengungkapkan identitas anak untuk kepentingan yang berpotensi merugikan mereka.
BACA JUGA: Alarm Bahaya Akibat Bullying yang Tak Terselesaikan
Namun persoalan terbesarnya bukan hanya hukum, melainkan etika. Anak-anak ini tumbuh dalam dunia yang mengabadikan setiap fase hidup mereka secara paksa. Tanpa sadar, sebagian orang tua menjadikan anak sebagai pusat konten demi pengakuan digital. Mereka lupa bahwa membesarkan anak bukan tentang eksposur, melainkan tentang rasa aman.
BACA JUGA:Rotasi Pejabat Jadi Ujian Nyata Transformasi Birokrasi Daerah
Toxic parenting di media sosial menciptakan generasi yang tumbuh dengan dua beban: tekanan untuk tampil sempurna, dan rasa malu atas rekaman masa kecilnya yang tak pernah mereka setujui. Padahal anak tidak membutuhkan viral, mereka membutuhkan ruang untuk menjadi manusia bukan materi konten.
BACA JUGA:Korupsi Adalah Adat
Sebagai orang dewasa, kita punya kewajiban moral untuk berhenti menjadikan sosial media sebagai arena kompetisi “siapa paling lucu”, “siapa paling parenting goals”, dan “siapa paling viral.” Karena di balik setiap unggahan anak, ada tanggung jawab jangka panjang yang tak bisa dibayar dengan likes.
Sumber: