Smart City Tanpa Smart People Hanya Jadi Proyek Hiasan
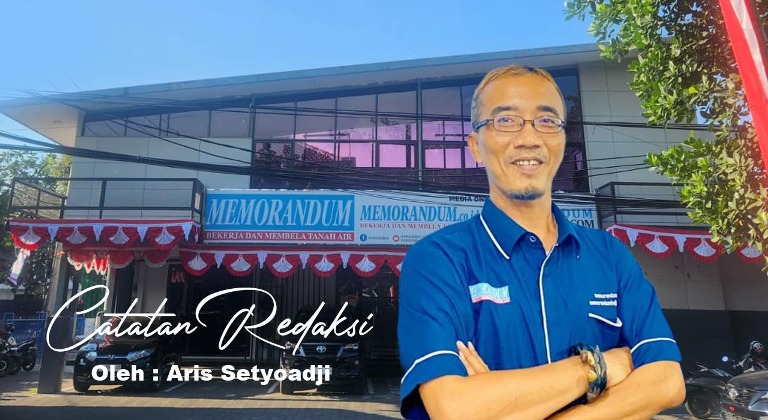
--
Istilah smart city telah menjadi populer dalam administrasi pemerintahan modern.
Hampir setiap daerah berlomba mengibarkan jargon teknologi sebagai tanda kemajuan.
Mulai dari pemasangan CCTV dengan kecerdasan buatan, pembangunan command center yang gemerlap, hingga peluncuran aplikasi layanan publik dalam jumlah yang tidak lagi terhitung.

Mini Kidi--
Namun, di balik euforia digital ini, muncul kenyataan pahit, kota pintar tidak otomatis lahir hanya karena perangkat teknologi dihadirkan.
Di banyak daerah, smart city justru berhenti sebagai proyek etalase.
Pemerintah membangun dashboard besar yang menampilkan peta, grafik, dan warna-warni data, tetapi isinya tidak pernah menjadi dasar pengambilan kebijakan.
BACA JUGA:Rotasi Pejabat Jadi Ujian Nyata Transformasi Birokrasi Daerah
Layar itu pada akhirnya berubah menjadi “TV raksasa” yang hanya difungsikan ketika ada kunjungan pejabat.
Di luar itu, ruangan gelap, layar mati, dan data menjadi hiasan modern yang tidak memiliki kontribusi nyata.
Ini memperlihatkan masalah mendasar, smart city tidak pernah benar-benar dirancang untuk menyelesaikan persoalan kota, melainkan untuk menyelesaikan persoalan citra pemerintah, karena teknologi dijadikan dekorasi, bukan instrumen transformasi.
Selain itu, pembangunan smart city sering dilakukan tanpa peta jalan yang jelas.
BACA JUGA:Bank Sampah dan Ilusi Hijau, Sudahkah Kita Jujur Mengelola Limbah
Banyak program lahir karena mengikuti tren atau kompetisi antar daerah, bukan karena analisis kebutuhan.
Padahal, kota yang memiliki masalah transportasi, sampah, kesehatan, atau pendidikan membutuhkan pendekatan berbeda.
Setiap solusi digital seharusnya bertumpu pada permasalahan prioritas, bukan pada teknologi yang kebetulan sedang populer.
Kesalahan berikutnya adalah pengabaian pada faktor manusia, sebab pemerintah membeli sistem digital berharga miliaran rupiah tetapi lupa memastikan siapa yang mampu mengelola, menganalisis, dan mengembangkan datanya.
BACA JUGA:Pesta di Surabaya Membuka Luka Lama
Aparatur yang bertugas sebagai operator tidak dibekali pelatihan memadai. Akibatnya, data masuk begitu saja tanpa disaring, tanpa diverifikasi, tanpa diolah menjadi rekomendasi kebijakan.
Sistem pintar tidak akan berguna jika dioperasikan oleh SDM yang tidak dipersiapkan untuk menjadi bagian dari ekosistem digital.
Dalam banyak kasus, operator hanya bertugas menjaga perangkat, bukan menggunakannya.
Situasi ini menciptakan kondisi ironi, karena smart city tidak dikelola oleh smart people, sehingga hasilnya tidak pernah smart.
Budaya kerja birokrasi yang lambat beradaptasi turut memperburuk situasi.
BACA JUGA:Zakat ASN, Energi Perubahan Kota Surabaya
Data yang seharusnya menjadi basis perumusan kebijakan sering kali tidak dipercaya.
Keputusan diambil berdasarkan intuisi dan tradisi, bukan berdasarkan bukti digital yang tersedia.
Ini menyebabkan teknologi kehilangan nilai karena tidak digunakan untuk fungsi strategis.
Masalah lain yang tidak kalah serius adalah fragmentasi aplikasi.
BACA JUGA:Keselamatan Bukan Pilihan tapi Kewajiban
Banyak daerah meluncurkan puluhan aplikasi layanan publik.
Setiap dinas ingin memiliki aplikasi sendiri karena dianggap sebagai simbol modernisasi.
Namun, aplikasi-aplikasi tersebut tidak saling terhubung, data terpecah ke banyak platform, sehingga sulit dipadukan untuk analisis menyeluruh.
Pada akhirnya, sebagian besar aplikasi ditinggalkan karena tidak digunakan warga atau tidak terintegrasi dengan sistem lain.
BACA JUGA:Antara Keseimbangan Data dan Hidup Nyata
Fragmentasi digital ini tidak hanya membuang anggaran, tetapi juga menambah beban administrasi.
Alih-alih memudahkan, masyarakat dipaksa mengunduh banyak aplikasi dengan fungsi mirip atau tumpang tindih.
Smart city seharusnya menyederhanakan, bukan mempersulit.
Dalam konteks governance, tantangan terbesar adalah kesinambungan.
Banyak program smart city mati begitu pergantian kepala daerah terjadi.
Setiap pemimpin ingin meninggalkan jejak, sehingga program pendahulu dihapus, diganti, atau dipreteli.
BACA JUGA:Surabaya Digital, Pungli Masih Kental
Akibatnya, smart city selalu dimulai dari nol setiap lima tahun sekali.
Tidak ada proses berkelanjutan, tidak ada akumulasi pengetahuan, dan tidak ada bangunan sistem yang utuh.
Hal ini menunjukkan bahwa yang kurang bukan teknologi, melainkan manajemen perubahan.
Tanpa komitmen lintas periode, smart city hanya akan menjadi festival proyek baru setiap pergantian rezim.
Di tengah berbagai masalah tersebut, idealisme smart city sering melebur menjadi slogan kosong.
Padahal, smart city seharusnya menempatkan manusia sebagai pusatnya.
BACA JUGA:Dari Kursi Kehormatan ke Kursi Pesakitan
Teknologi adalah alat, bukan tujuan, karena tujuan utama adalah membangun tata kelola berbasis data, meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperkuat partisipasi publik, dan memberikan layanan yang mudah, cepat, serta transparan.
Konsep smart city yang benar mestinya dimulai dari membangun budaya organisasi yang menghargai data.
Aparatur harus didorong menjadi pembelajar, bukan sekadar pelaksana tugas.
Data harus menjadi bahan perumusan kebijakan, bukan sekadar angka di layar dashboard. Ketika budaya kerja berubah, barulah teknologi dapat berfungsi sebagai katalis.
Selain itu, masyarakat harus dilibatkan sejak awal, warga adalah pengguna utama layanan publik, sehingga desain teknologi harus menyesuaikan kebutuhan mereka.
BACA JUGA:Tubuh yang Tidak Bergerak
Banyak aplikasi gagal karena dibangun tanpa riset pengguna, smart city tidak akan berhasil jika masyarakat tidak merasa dilibatkan atau tidak memahami manfaatnya.
Pemerintah juga perlu membangun integrasi digital lintas sektor, data kesehatan harus terhubung dengan data kependudukan.
Data transportasi terhubung dengan data infrastruktur.
Data pendidikan terhubung dengan data sosial.
Dengan integrasi, pemerintah dapat melihat persoalan secara menyeluruh dan membuat kebijakan yang lebih presisi.
Untuk itu, dibutuhkan arsitektur data yang matang.
BACA JUGA:Redenominasi Rupiah
Setiap sistem digital harus berbicara dalam satu bahasa data yang sama, standarisasi sangat penting agar data tidak tercerai-berai.
Pada akhirnya, smart city bukan tentang ruang kendali canggih atau aplikasi berwarna cerah.
Smart city adalah tentang kemampuan pemerintah membaca, memahami, dan merespons persoalan secara cepat, tepat, dan berbasis bukti.
Jika sisi ini tidak diperkuat, seluruh investasi teknologi hanya menjadi monumen modern yang tidak memberi efek perubahan.
Perubahan selalu dimulai dari visi yang jelas, membangun pemerintahan berbasis data dan layanan publik yang melayani, bukan mempersulit.
BACA JUGA:Suporter Bukan Customer
Jika visi itu dipegang, maka teknologi digital akan berubah menjadi mesin perubahan.
Bila tidak, teknologi akan terus menjadi pajangan mahal yang sulit dipertanggungjawabkan manfaatnya.
Smart city hanya akan berarti ketika manusia yang mengelolanya memiliki kemampuan, integritas, dan kesadaran bahwa teknologi adalah alat untuk memperbaiki kehidupan, bukan alat untuk mempercantik laporan.
Sumber:






















